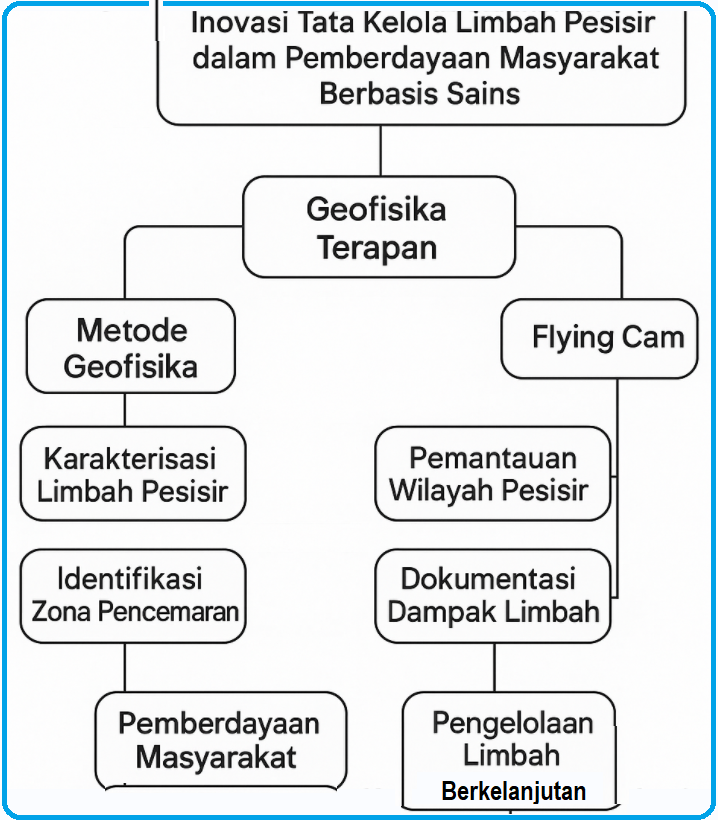Sub judul : "Transformasi Limbah Cangkang Kerang, Kepah, & Tulang Ikan Menjadi Produk Bernilai Tambah Membantu Program Pemerintah Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Angka Prevalensi Stunting melalui Zero Waste, Sirkular Ekonomi, Model Kolaborasi Hepta Helix, SDG’s, Ekonomi Hijau & Biru & Proper Gold ".
oleh :
1. Dr. H. Marhaban
Sigalingging, Dosen di Universitas Muhammadiyah Metro. Local Business, MPP ICMI
Dewan Pakar Ekonomi & Inovasi Jakarta. Periode 2021-2026, CEO Marhaban
Corp.
2. KH. Dr.
Muhammad Sontang Sihotang S.Si, M.Si*.(Alumnus S-1 : Fisika USU ’88, S-2
Alumnus: Materials Science-University of Indonesia (UI) Salemba, Central
Jakarta Alumnus S-3 ; Universiti Zainal Abidin (UniSZA) Kuala Terengganu,
Malaysia, Bidang Kajian : Metafisika Tasawuf, Kepala Laboratorium Fisika
Nuklir, Prodi Fisika, Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam, Peneliti
Pusat Unggulan Ipteks Karbon & Kemenyan-Universitas Sumatera Utara
(USU)-Medan, Dosen Prodi Ilmu Filsafat Universitas Pembangunan Panca Budi
(UNPAB)-Medan, Mantan Dosen Sains Fizik / Quantum Physics, Fisika Kelautan,
Food & Technology Physics, Fakulti Sains dan Teknologi (FST), Universiti
Malaysia Terengganu (UMT), Malaysia, Tahun 2007-2013, Mantan Dosen Fisika
Kedokteran & Keperawatan, Fakultas Kedokteran & Fakultas Ilmu
Keperawatan Universitas Indonesia (FIK-UI), d/h Salemba, Jakarta Pusat, Tahun
1996 s.d 2000. Fellowship & Training in Medical Image Processing &
Computing (MIPC) @ Vrije University Brussels (VUB)-Belgium (VLIR Scholarship)
& Institute Science & Medical (ISM)- Salzburg-Austria-Tahun 2000/2001,
Bagian Fisika Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas YARSI, Cempaka Putih,
Jakarta Pusat, Tahun 2000-2004, Manager Engineering Data & Information
Centre (EDIC) Engineering Centre, Fakultas Teknik – Universitas Indonesia-
Depok (2005-2006), Wartawan PortalMedan News.
Abstrak :
Kemajuan teknologi
flying cam (drone) dan pendekatan geofisika terapan telah membuka peluang baru
dalam pengelolaan sumber daya & limbah pesisir berbasis data spasial.
Artikel ini
membahas pemanfaatan flying cam oleh masyarakat peneliti geofisika dalam
memetakan dan mengelola limbah organik pesisir seperti cangkang kerang, kepah
& tulang ikan di desa pesisir, khususnya dalam konteks pengentasan
kemiskinan ekstrem & penurunan angka stunting. Melalui identifikasi lokasi
limbah, analisis kandungan mineral & transformasi material berbasis kalsium
menjadi produk bernilai tambah (seperti granular pupuk, suplemen gizi & kerajinan biokomposit), riset ini mendukung
implementasi prinsip zero waste, ekonomi sirkular, ekonomi hijau-biru, SDG’s serta
model kolaborasi Hepta Helix.
Hasilnya akan menunjukkan
bahwa integrasi teknologi geospasial & pemberdayaan komunitas pesisir dapat
menjadi strategi inovatif dalam mencapai target SDG’s, PROPER Gold, dan
kemandirian desa berbasis sains.
Kata Kunci: Flying
Cam, Geofisika Terapan, Limbah Pesisir, Cangkang Kerang, Tulang Ikan, Ekonomi
Sirkular, Pemberdayaan Masyarakat, Zero Waste, SDG’s, Hepta Helix, Ekonomi Hijau
– Biru.
Pendahuluan
:
Sains untuk
Masyarakat Pesisir yang Tangguh, Pesisir bukan hanya batas daratan & lautan, melainkan ruang hidup strategis dengan
potensi ekonomi & ekologis yang besar. Namun, wilayah ini juga kerap
menjadi episentrum masalah : limbah organik dari hasil laut menumpuk,
kemiskinan ekstrem masih tinggi & angka stunting di komunitas pesisir tetap
memprihatinkan.
Dalam konteks
inilah geofisika terapan & teknologi flying cam (drone) hadir sebagai
instrumen ilmiah yang tidak hanya mencatat, tetapi juga mengubah keadaan.
Artikel ini
mengeksplorasi bagaimana pendekatan berbasis sains, khususnya geofisika terapan
& pemetaan udara, berkontribusi dalam pengelolaan limbah pesisir, seperti
cangkang kerang, kepah & tulang ikan, menjadi produk inovatif bernilai
tambah.
Upaya ini
mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka prevalensi
stunting, serta pembangunan berkelanjutan berbasis prinsip zero waste, sirkular
ekonomi, SDG’s, Ekonomi hijau-biru Model Hepta Helix Collaboration.
Permasalahan :
Wilayah pesisir di
Indonesia menyimpan potensi sumber daya hayati dan mineral yang besar, tetapi
pada saat yang sama menghadapi berbagai permasalahan krusial yang bersifat
multidimensi. Salah satu tantangan utama adalah masih belum optimalnya
pemanfaatan limbah pesisir organik, seperti cangkang kerang, kepah & tulang
ikan, yang sering kali terakumulasi & menjadi sumber pencemaran lingkungan.
Padahal, material tersebut kaya akan kandungan kalsium yang berpotensi untuk
diolah menjadi produk inovatif bernilai ekonomi tinggi seperti pupuk organik,
bio-material, dan suplemen pakan.
Di sisi lain,
ketimpangan data spasial terkait distribusi dan volume limbah, keterbatasan
akses teknologi, serta minimnya pendekatan ilmiah dalam perencanaan tata kelola
limbah menjadi hambatan dalam upaya pengelolaan yang berkelanjutan. Teknologi
geospasial seperti flying cam (drone) belum banyak diadopsi secara sistematis
dalam survei dan penelitian berbasis masyarakat di kawasan pesisir.
Masalah
tersebut diperparah oleh:
Kurangnya
integrasi riset geofisika dengan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam aspek
hilirisasi hasil riset ke produk inovatif;
Rendahnya literasi
teknologi & sains di kalangan masyarakat pesisir, khususnya perempuan &
kelompok marjinal;
Belum adanya model
kolaborasi multipihak (Hepta Helix) yang komprehensif dalam menangani masalah
limbah pesisir dari hulu ke hilir;
Masih tingginya
angka kemiskinan ekstrem & stunting di desa-desa pesisir, yang seharusnya
bisa ditekan dengan pendekatan ekonomi sirkular & pemanfaatan sumber daya
lokal.
Dengan latar
belakang tersebut, diperlukan model inovatif berbasis ilmu geofisika, didukung
teknologi flying cam, serta pendekatan pemberdayaan komunitas yang
mengintegrasikan pengelolaan limbah pesisir dengan agenda pembangunan
berkelanjutan (SDG’s), ekonomi biru, ekonomi hijau, dan sistem pendampingan
yang kolaboratif.
Alternatif
Penyelesaian Masalah :
Untuk menjawab
kompleksitas masalah pengelolaan limbah pesisir organik & rendahnya
pemanfaatan teknologi sains dalam pengembangan desa pesisir, berikut beberapa
alternatif penyelesaian yang dapat ditawarkan secara terintegrasi & berkelanjutan:
1. Penerapan
Teknologi Flying Cam dalam Pemetaan Spasial Limbah, Drone atau flying cam dapat
dimanfaatkan untuk:
Memetakan
titik-titik akumulasi limbah pesisir (cangkang kerang, kepah & tulang
ikan);
Menghasilkan citra
spasial berkala yang membantu perencanaan zona pengumpulan & pengolahan;
Mendukung survei
geofisika awal dengan akurasi tinggi untuk mendeteksi potensi lingkungan bawah
permukaan.
Manfaat :
efisiensi survei lapangan, data akurat untuk perencanaan, serta dokumentasi
visual yang mudah dianalisis & dibagikan.
2. Integrasi
Geofisika Terapan dalam Riset & Pengembangan Produk
Pendekatan
geofisika terapan seperti resistivitas, GPR & analisis mineral dapat
digunakan untuk:
Mengidentifikasi
kualitas & kandungan kalsium dalam limbah organik;
Menentukan lokasi
terbaik untuk fasilitas pengolahan limbah;
Mendukung validasi
produk inovasi seperti granular kalsium, pupuk organik, atau biomaterial.
Manfaat :
menjembatani riset ilmiah & pemanfaatan praktis yang berbasis pada potensi
lokal.
3. Pengembangan
Produk Inovatif Berbasis Zero Waste & Ekonomi Sirkular
Transformasi
limbah organik menjadi:
Granular pupuk
organik kaya kalsium
Suplemen pakan
ternak & unggas
Produk kerajinan
bio-komposit ramah lingkungan
Bahan dasar
biokeramik atau campuran semen hijau
Manfaat :
meningkatkan nilai ekonomi limbah, membuka peluang UMKM local & mendorong
model ekonomi berkelanjutan.
4. Penguatan
Kapasitas Masyarakat dan Literasi Teknologi
Melalui pelatihan
dan pendampingan kepada masyarakat (terutama perempuan pesisir) dalam:
Penggunaan &
pemeliharaan flying cam;
Teknik dasar
geofisika partisipatif;
Proses pengolahan
limbah menjadi produk bernilai tambah;
Pemasaran & manajemen
usaha mikro.
Manfaat:
peningkatan kapasitas lokal, pemberdayaan ekonomi berbasis keterampilan, dan
kemandirian desa pesisir.
5. Pembentukan
Model Kolaborasi Hepta Helix dalam Tata Kelola ; Mendorong sinergi antara: Akademisi
(riset dan teknologi), Pemerintah (regulasi dan insentif), Dunia usaha (hilirisasi
produk dan investasi), Masyarakat (produksi dan pemanfaatan), Media (publikasi
dan edukasi), Lembaga keuangan (pembiayaan inklusif), LSM dan filantropi
(pendampingan berkelanjutan).
Manfaat:
kolaborasi lintas sektor yang terstruktur, mendorong keberlanjutan program dan
akselerasi dampak sosial-lingkungan.
6. Integrasi
dengan Program Nasional: SDGs, Ekonomi Hijau–Biru, dan PROPER
Menjadikan program
ini bagian dari pencapaian Sustainable Development Goals;
Mengusulkan model
desa pesisir sebagai pilot project ekonomi hijau–biru;
Mendukung
pencapaian PROPER Emas dalam pengelolaan lingkungan berbasis inovasi dan
pemberdayaan.
Manfaat:
meningkatkan posisi strategis desa dalam pembangunan nasional dan penguatan
reputasi lingkungan secara global.
Tujuan Kajian
Kajian ini
bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi flying cam dan pendekatan geofisika
terapan dalam pengelolaan limbah pesisir berbasis cangkang kerang, kepah, dan
tulang ikan, guna mendorong inovasi produk lokal serta pemberdayaan masyarakat
pesisir secara berkelanjutan dalam kerangka SDGs, ekonomi sirkular, dan model
kolaborasi Hepta Helix.
Objektif Kajian
Menganalisis
potensi penggunaan flying cam (drone) untuk pemetaan spasial limbah organik di
wilayah pesisir.
Mengkaji aplikasi
geofisika terapan dalam mengidentifikasi lokasi, kandungan mineral, dan
karakteristik limbah cangkang dan tulang ikan.
Merancang strategi
pemanfaatan limbah pesisir menjadi produk bernilai tambah, seperti granular
kalsium, pupuk, dan bio-material.
Menawarkan model
pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis teknologi dan inovasi lokal, khususnya
melalui keterlibatan perempuan dan kelompok marginal.
Mengusulkan
kerangka kolaborasi multipihak (Hepta Helix) dalam pengelolaan limbah pesisir
yang terukur, berkelanjutan, dan berbasis data ilmiah.
Manfaat Kajian
Manfaat Teoritis:
Menambah khazanah
keilmuan dalam bidang geofisika terapan, geospasial, dan teknologi pesisir
berbasis drone.
Memberikan
perspektif interdisipliner antara ilmu kebumian, teknologi lingkungan, dan
pemberdayaan sosial.
Manfaat Praktis:
Memberikan model
aplikatif bagi pemerintah desa dan komunitas pesisir dalam memanfaatkan limbah
lokal secara produktif.
Menyediakan dasar
ilmiah dan spasial untuk perencanaan program desa berbasis ekonomi sirkular dan
zero waste.
Meningkatkan
kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan teknologi sederhana namun berdampak
tinggi.
Mendorong
kolaborasi sektor swasta, akademisi, dan komunitas dalam pembangunan desa
berbasis inovasi lokal.
Batasan Kajian :
Ruang lingkup
wilayah terbatas pada desa-desa pesisir yang memiliki sumber limbah organik
laut seperti cangkang kerang, kepah, dan tulang ikan (contohnya: Desa Medang,
Kab. Batubara).
Teknologi flying
cam yang dikaji dibatasi pada penggunaan untuk pemetaan spasial (fotogrametri
dan citra visual), belum mencakup drone dengan sensor LiDAR atau hyperspectral.
Aspek geofisika
difokuskan pada aplikasi survei permukaan dan near-surface (resistivitas dan
GPR) yang relevan untuk mendukung pemetaan dan analisis kandungan limbah.
Pengolahan limbah
dibatasi pada transformasi menjadi produk turunan berbasis kalsium tanpa
membahas pengolahan limbah non-organik atau industri skala besar.
Pendekatan
kolaborasi dibahas dalam kerangka konseptual dan implementatif, namun belum
pada tahap evaluasi dampak kuantitatif secara jangka panjang.
Kajian Sebelumnya :
Kajian ilmiah
terkait pemanfaatan teknologi flying cam (drone) dan pendekatan geofisika dalam
pengelolaan wilayah pesisir serta pemberdayaan masyarakat menunjukkan
perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa penelitian
terdahulu menjadi dasar penting bagi pengembangan model integratif berbasis
sains ini.
1. Penggunaan
Drone dalam Pemetaan Pesisir dan Lingkungan
Menurut Wahyudi
& Lestari (2023), drone telah terbukti efektif dalam melakukan pemetaan
wilayah pesisir yang rentan terhadap perubahan seperti abrasi, sedimentasi, dan
pencemaran. Teknologi ini mampu menyediakan citra spasial berkualitas tinggi
secara cepat dan efisien, termasuk untuk mengidentifikasi distribusi limbah di
zona intertidal dan pesisir dangkal.
Penelitian
Rahmadani et al. (2022) juga menunjukkan bahwa drone mendukung survei lapangan
berbasis komunitas dalam program mitigasi bencana pesisir dengan menurunkan
risiko keselamatan tim survei dan meningkatkan akurasi pemetaan kawasan rawan.
2. Aplikasi
Geofisika Terapan di Wilayah Pesisir
Dalam ranah ilmu
kebumian, BRIN (2022) mengembangkan pendekatan geofisika terapan dengan
memanfaatkan resistivitas dan GPR (Ground Penetrating Radar) untuk mendeteksi
struktur bawah permukaan di kawasan pesisir dan tambak. Teknologi ini sangat
relevan dalam mendukung identifikasi zona akumulasi limbah dan sumber daya
mineral lokal, termasuk kandungan kalsium dari limbah organik laut seperti
tulang ikan dan cangkang kerang.
3. Potensi Limbah
Organik Pesisir sebagai Produk Bernilai Tambah
Penelitian oleh
Rinaldi et al. (2023) mengemukakan bahwa cangkang kerang, kepah, dan tulang
ikan kaya akan kandungan kalsium karbonat (CaCO₃) dan kalsium fosfat
(Ca₁₀(PO₄)₆(OH)₂), yang dapat diolah menjadi produk bio-material, pupuk
organik, suplemen pakan, hingga bahan dasar biokeramik. Namun, masih terdapat
kesenjangan dalam hal integrasi antara data spasial dan proses pengolahan
limbah tersebut dalam skala komunitas.
4. Ekonomi
Sirkular dan Zero Waste di Pesisir
Kajian oleh Sari
& Nugroho (2021) menggarisbawahi pentingnya pendekatan ekonomi sirkular dan
konsep zero waste dalam pengelolaan limbah pesisir. Mereka menyarankan perlunya
inovasi berbasis lokal dan pendekatan lintas ilmu yang mampu memberdayakan
masyarakat sambil menjaga kelestarian lingkungan.
5. Model
Kolaboratif dalam Pemberdayaan Komunitas
Pendekatan
pembangunan kolaboratif berbasis Penta Helix telah banyak dikaji dalam konteks
desa wisata, konservasi, dan inovasi UMKM. Namun, Utami (2020) menunjukkan
bahwa model Hepta Helix, yang menambahkan sektor keuangan dan lembaga
filantropi ke dalam kolaborasi, memiliki potensi lebih besar dalam mendorong
inovasi berbasis komunitas – tetapi masih jarang diterapkan dalam konteks
pengelolaan limbah pesisir.
Dari berbagai
kajian tersebut, terlihat adanya pemisahan antara riset teknologi (flying cam
dan geofisika), riset potensi limbah organik, dan kajian sosial pemberdayaan
masyarakat. Belum banyak studi yang mengintegrasikan ketiganya dalam satu
pendekatan terpadu untuk menjawab permasalahan pesisir secara holistik. Oleh
karena itu, artikel ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan merancang
suatu model inovatif berbasis geosains, teknologi drone, dan kolaborasi
multi-aktor untuk mendorong transformasi lingkungan, sosial, dan ekonomi di
kawasan pesisir.
State of the Art :
Dalam beberapa
tahun terakhir, pemanfaatan teknologi drone (flying cam) dan pendekatan
geofisika terapan telah mengalami kemajuan pesat, khususnya dalam konteks riset
wilayah pesisir dan pengelolaan lingkungan. Drone kini tidak lagi terbatas
sebagai alat dokumentasi visual, melainkan telah berevolusi menjadi instrumen
penting dalam pengumpulan data spasial, pemetaan topografi, pemantauan
perubahan garis pantai, serta deteksi akumulasi limbah organik secara presisi.
Hal ini menjadikan teknologi drone sebagai salah satu pilar penting dalam
modernisasi riset geospasial pesisir.
Di sisi lain, ilmu
geofisika terapan terus berkembang dari sekadar eksplorasi sumber daya bawah
tanah menjadi pendekatan transdisipliner yang mendukung pemetaan lingkungan,
mitigasi bencana, serta tata ruang berbasis karakteristik geologis lokal. Dalam
konteks pesisir, metode seperti resistivity mapping dan Ground Penetrating
Radar (GPR) telah dimanfaatkan untuk memetakan area abrasi, sebaran sedimen,
dan struktur tanah dangkal — termasuk area akumulasi limbah berbasis kalsium
seperti tulang ikan, cangkang kerang, dan kepah.
Bersamaan dengan
perkembangan tersebut, konsep zero waste dan ekonomi sirkular telah menjadi
arah baru dalam pengelolaan limbah organik, termasuk limbah laut. Riset
sebelumnya (Rinaldi et al., 2023) menunjukkan bahwa limbah cangkang dan tulang
ikan mengandung mineral penting seperti CaCO₃ dan Ca₁₀(PO₄)₆(OH)₂, yang sangat
potensial untuk diolah menjadi pupuk organik, suplemen pakan, biokomposit, dan
bahan dasar bio-keramik. Namun, kebanyakan kajian masih bersifat sektoral dan
belum mengintegrasikan pemetaan spasial, pengolahan berbasis geosains, dan
strategi pemberdayaan masyarakat secara komprehensif.
Selain itu, model
pembangunan kolaboratif berbasis Hepta Helix (akademisi, pemerintah, pelaku
usaha, komunitas, media, lembaga keuangan, dan filantropi) mulai diadopsi dalam
proyek-proyek pembangunan berkelanjutan. Meski begitu, penerapannya dalam
konteks pengelolaan limbah pesisir berbasis teknologi flying cam dan riset
geofisika masih sangat terbatas.
Oleh karena itu,
posisi artikel ini menjadi penting karena menyatukan tiga pilar utama yang
jarang dikombinasikan dalam satu kerangka ilmiah dan implementatif, yaitu:
Teknologi pemetaan
udara (drone/flying cam) untuk survei dan dokumentasi limbah pesisir;
Geofisika terapan
sebagai pendekatan ilmiah dalam menilai potensi kandungan dan distribusi limbah
berbasis mineral;
Pemberdayaan
masyarakat pesisir berbasis ekonomi sirkular, zero waste, dan kolaborasi Hepta
Helix untuk mewujudkan desa mandiri dan berkelanjutan.
Dengan demikian,
artikel ini menempati posisi state of the art sebagai upaya lintas-disiplin
yang mengisi kekosongan antara teknologi mutakhir, pemanfaatan sumber daya
lokal, dan strategi pembangunan masyarakat berbasis data dan inovasi.
Grand Theory :
Kajian ini
berpijak pada landasan teoritis interdisipliner yang menggabungkan tiga
pendekatan besar, yaitu Teori Sistem Sosial-Ekologis (Social-Ecological Systems
Theory), Teori Inovasi Teknologi (Diffusion of Innovation Theory), dan Teori
Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment Theory). Ketiganya membentuk kerangka
pikir integratif yang menopang pengembangan model pengelolaan limbah pesisir
berbasis teknologi flying cam dan geofisika terapan dalam konteks pembangunan
berkelanjutan.
1. Teori Sistem
Sosial-Ekologis (SES Theory) – Elinor Ostrom
Teori ini
menjelaskan bahwa wilayah pesisir merupakan suatu sistem kompleks yang terdiri
dari interaksi antara manusia (masyarakat pesisir), sumber daya alam (limbah
laut organik), dan institusi (pemerintah, komunitas lokal). Dalam konteks ini,
keberhasilan pengelolaan limbah tidak hanya bergantung pada aspek teknis,
tetapi juga pada dinamika sosial dan kelembagaan yang mengatur akses,
penggunaan, dan pemanfaatannya secara berkelanjutan.
Implikasi:
Pendekatan geofisika dan teknologi flying cam akan efektif jika dikontekstualisasikan
dalam sistem sosial-ekologis lokal yang adaptif, partisipatif, dan berlandaskan
nilai-nilai komunitas.
2. Teori Difusi
Inovasi (Diffusion of Innovation Theory) – Everett M. Rogers
Rogers menekankan
bahwa penyebaran inovasi dalam masyarakat sangat bergantung pada karakteristik
teknologi (sederhana, terjangkau, bermanfaat), saluran komunikasi, dan kesiapan
sosial-budaya penerima inovasi. Drone dan geofisika sebagai teknologi modern
dapat diadopsi oleh masyarakat pesisir jika disosialisasikan melalui pendekatan
partisipatif, pelatihan aplikatif, dan dukungan kelembagaan.
Implikasi: Agar
flying cam dan geofisika dapat diterima dan diadopsi, dibutuhkan strategi
capacity building, komunikasi lintas aktor, dan adaptasi teknologi dengan
kearifan lokal.
3. Teori
Pemberdayaan Komunitas (Community Empowerment Theory) – Zimmerman &
Rappaport
Teori ini
menjelaskan pentingnya transfer kontrol, pengetahuan, dan keterampilan kepada
masyarakat lokal agar mereka mampu mengambil keputusan, mengelola sumber daya,
dan meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Dalam konteks ini, pengelolaan
limbah pesisir bukan semata urusan teknis, tetapi proses kolektif yang
meningkatkan self-efficacy, ownership, dan partisipasi masyarakat — khususnya
perempuan dan kelompok rentan.
Implikasi:
Pengolahan limbah berbasis flying cam dan geofisika harus melibatkan masyarakat
dalam setiap tahap: dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Sintesis Grand
Theory :
Ketiga teori
tersebut diintegrasikan dalam satu kerangka berpikir yang menekankan bahwa:
Inovasi teknologi
(drone & geofisika) hanya efektif jika ditanamkan dalam sistem
sosial-ekologis yang partisipatif;
Pengelolaan limbah
harus berbasis data ilmiah dan sensitivitas lokal;
Pemberdayaan
masyarakat menjadi kunci keberlanjutan inovasi lingkungan dan ekonomi, terutama
di wilayah pesisir yang rentan.
Model yang
diusulkan dalam artikel ini mendukung capaian SDGs (Sustainable Development
Goals), prinsip ekonomi hijau dan biru, serta tata kelola kolaboratif dalam
skema Hepta Helix sebagai operasionalisasi nyata dari grand theory tersebut.
Metodologi :
Penelitian ini
menggunakan pendekatan interdisipliner dan partisipatif yang menggabungkan
metode kuantitatif (pengukuran geofisika dan pemetaan drone) serta kualitatif
(wawancara, FGD, observasi lapangan) dalam satu kerangka riset terapan berbasis
pemberdayaan masyarakat. Penelitian dilaksanakan di wilayah pesisir yang
memiliki potensi limbah organik laut seperti cangkang kerang, kepah, dan tulang
ikan, dengan fokus pada pengembangan teknologi tepat guna dan model kolaboratif
pengelolaannya.
1. Lokasi dan
Subjek Penelitian
Lokasi : Desa
pesisir yang aktif dalam aktivitas perikanan dan pengolahan hasil laut, seperti
Desa Medang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.
Subjek : Peneliti
geofisika, operator drone, pelaku UMKM lokal, perempuan pengupas kerang, tokoh
desa, dan stakeholder lainnya (pemerintah desa, akademisi, pengusaha lokal).
2. Teknik
Pengumpulan Data
Pengumpulan data
dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa pendekatan terintegrasi.
Pertama, dilakukan
pemetaan udara menggunakan flying cam (drone) untuk memperoleh data spasial dan
visual terkait sebaran limbah organik pesisir, seperti cangkang kerang, kepah,
dan tulang ikan. Penggunaan drone ini memungkinkan pengambilan citra secara
presisi dan real-time yang kemudian diolah menggunakan perangkat lunak
fotogrametri dan sistem informasi geografis (SIG).
Kedua, untuk
memperoleh data bawah permukaan, dilakukan survei geofisika dengan metode
resistivitas dan Ground Penetrating Radar (GPR). Teknik ini bertujuan untuk
mengidentifikasi karakteristik fisik dan geologi dangkal pada wilayah pesisir
yang berpotensi sebagai lokasi akumulasi limbah atau tempat pengolahan berbasis
kalsium.
Ketiga,
dikumpulkan pula data sosial dan ekonomi melalui observasi langsung di
lapangan, wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat dan pelaku usaha lokal,
serta diskusi kelompok terfokus (FGD) bersama komunitas perempuan pesisir dan
pengelola UMKM. Metode ini digunakan untuk menggali informasi terkait praktik
lokal dalam pengelolaan limbah, persepsi masyarakat terhadap inovasi teknologi,
serta peluang dan hambatan pemberdayaan.
Keempat, dilakukan
pengambilan sampel limbah (tulang ikan, cangkang kerang, dan kepah) untuk dianalisis
di laboratorium. Analisis ini bertujuan untuk mengukur kandungan kalsium
karbonat (CaCO₃) dan kalsium fosfat (Ca₁₀(PO₄)₆(OH)₂) sebagai dasar
pengembangan produk inovatif berbasis mineral lokal.
3. Teknik Analisis
Data
Analisis spasial:
Menggunakan software GIS (ArcGIS/QGIS) dan fotogrametri (DroneDeploy/Agisoft)
untuk pemetaan distribusi limbah.
Analisis
geofisika: Interpretasi data resistivitas dan GPR untuk mengetahui kedalaman
dan potensi sebaran limbah mineral lokal.
Analisis
laboratorium: Uji kuantitatif kandungan kalsium dengan metode titrasi
kompleksometri dan spektrofotometri.
Analisis sosial:
Koding tematik dan matriks SWOT dari wawancara dan FGD untuk menggambarkan
persepsi masyarakat, tantangan, dan peluang pengelolaan limbah.
Sintesis model
integratif: Penggabungan semua hasil ke dalam satu desain model tata kelola
berbasis teknologi, partisipasi, dan kolaborasi multipihak (Hepta Helix).
4. Validasi dan
Uji Coba
Model diuji coba
secara terbatas dalam bentuk:
Demonstrasi
teknologi drone & geofisika kepada masyarakat;
Pelatihan
pengolahan limbah berbasis hasil laboratorium;
Simulasi
kolaborasi antar-helix dengan menghadirkan unsur akademik, bisnis, pemerintah,
dan komunitas dalam satu forum lokakarya desa.
5. Etika
Penelitian
Seluruh proses
dilaksanakan dengan persetujuan dan keterlibatan aktif masyarakat lokal.
Peneliti memastikan prinsip partisipatif, transparan, dan non-eksploitatif,
dengan menghormati kearifan lokal dan hak masyarakat atas data dan manfaat.
Bahan dan
Peralatan :
Untuk mendukung
proses penelitian yang bersifat multidisipliner ini, digunakan berbagai bahan
dan peralatan yang mencakup bidang geospasial, geofisika, dan laboratorium
kimia, serta alat bantu dalam kegiatan sosial-partisipatif masyarakat.
1. Bahan
Penelitian:
Limbah organik
pesisir:
Cangkang kerrang, Kepah,
Tulang ikan
(khususnya ikan tamban, tongkol, dan kembung)
Reagen
laboratorium:
Larutan EDTA
(untuk analisis kalsium)
Buffer larutan pH
Indikator
Eriochrome Black T
Aquades dan
larutan standar Ca²⁺
Media dokumentasi
dan pelatihan:
Kuesioner
wawancara
Leaflet dan poster
edukasi pengolahan limbah
Modul pelatihan
teknologi tepat guna
2. Peralatan Penelitian:
A. Geospasial dan
Drone:
Drone quadcopter
dan/atau fixed-wing dengan kamera HD (misalnya DJI Phantom 4 Pro atau sejenis)
Kontroler dan
tablet monitor penerbangan
Perangkat lunak
pemrosesan citra: Agisoft Metashape, DroneDeploy, atau Pix4D
Komputer/laptop
dengan spesifikasi tinggi untuk pengolahan data citra dan peta
B. Geofisika
Terapan:
Alat Resistivitas
Multi-Elektroda (misalnya ARES atau PASI)
Alat Ground
Penetrating Radar (GPR) dengan antena frekuensi menengah
GPS Geodetik dan
Kompas Geologi
Kabel elektroda,
besi elektroda, palu, dan larutan garam untuk konektivitas tanah
C. Analisis
Laboratorium:
Timbangan digital
presisi
Oven pengering dan
furnace (tanur pembakaran)
Mortar dan grinder
(penggiling bahan kering)
Spektrofotometer
UV-Vis atau AAS (Atomic Absorption Spectrophotometer)
Gelas ukur, buret,
pipet tetes, dan alat titrasi manual
D. Pendukung
Lapangan dan Partisipasi Masyarakat:
Alat perekam suara
dan kamera dokumentasi
Sound system
portable untuk pelatihan luar ruang
Spanduk edukasi
dan alat peraga visual
Buku catatan
lapangan, papan tulis mini, dan ATK
Rencana Hasil dan
Pembahasan
Dalam kajian ini,
hasil dan pembahasan direncanakan untuk disajikan dalam beberapa bagian utama
yang menggambarkan keterpaduan antara teknologi, data ilmiah, dan strategi
pemberdayaan masyarakat. Hasil yang diperoleh akan dibandingkan dengan
penelitian-penelitian sebelumnya serta dianalisis secara kritis berdasarkan
pendekatan transdisipliner dan lokalitas wilayah pesisir yang dikaji.
1. Hasil Pemetaan
Spasial Limbah Pesisir Menggunakan Flying Cam
Hasil utama yang
diharapkan adalah peta sebaran limbah organik pesisir (cangkang kerang, kepah,
tulang ikan) berdasarkan dokumentasi visual drone. Citra drone akan digunakan
untuk menunjukkan lokasi konsentrasi limbah tertinggi, potensi zona
pengumpulan, serta analisis overlay dengan faktor lingkungan seperti
pasang-surut, jarak ke pemukiman, dan akses jalan desa.
Analisis 1 :
Dibahas mengenai
efektivitas flying cam sebagai alat pemetaan alternatif yang efisien, murah,
dan akurat untuk mendukung perencanaan tata kelola limbah berbasis spasial di
desa pesisir.
2. Hasil Survei
Geofisika Terapan (Resistivitas dan GPR)
Survei ini akan
menghasilkan data visual dan numerik terkait kondisi bawah permukaan (tanah,
kandungan mineral, kelembapan, porositas) di lokasi-lokasi yang telah dipetakan
oleh drone. Data resistivitas dan GPR akan menunjukkan kesesuaian lahan untuk
pengolahan dan penyimpanan limbah berbasis kalsium.
Analisis 2 :
Bagaimana data
geofisika digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan teknis dalam
pengolahan limbah pesisir secara ilmiah, termasuk keunggulan penggunaan metode
geofisika non-destruktif di lingkungan desa.
3. Hasil Analisis
Kandungan Kalsium Limbah Organik
Analisis
laboratorium akan menunjukkan kandungan CaCO₃ pada cangkang kerang dan kepah,
serta Ca₁₀(PO₄)₆(OH)₂ pada tulang ikan. Kandungan ini menjadi dasar untuk
pengembangan produk inovatif seperti pupuk granular kalsium, bio-material, atau
bahan kerajinan fungsional.
Pembahasan 1 :
Dibahas potensi
limbah laut sebagai sumber bahan baku alternatif yang selama ini terabaikan.
Disandingkan pula dengan referensi hasil penelitian sebelumnya dan potensi
pengembangannya di skala UMKM atau industri rumah tangga.
4. Hasil
Partisipasi dan Persepsi Masyarakat Pesisir
Dari observasi,
wawancara, dan FGD, akan diperoleh informasi tentang pengetahuan, sikap, dan
praktik masyarakat dalam pengelolaan limbah organik, serta respons mereka
terhadap teknologi flying cam dan konsep pemberdayaan berbasis sains.
Pembahasan 2 :
Dibahas pentingnya
pendekatan partisipatif dalam memperkenalkan inovasi teknologi dan strategi
pemberdayaan yang tidak sekadar teknis tetapi juga membangun rasa memiliki
(ownership) dan keberlanjutan sosial.
5. Perumusan Model
Tata Kelola Limbah Pesisir Berbasis Hepta Helix
Hasil integrasi
seluruh data dan analisis digunakan untuk menyusun model tata kelola limbah
pesisir berbasis data spasial, geofisika, teknologi drone, dan kolaborasi
multipihak (Hepta Helix). Model ini akan divisualisasikan dalam bentuk diagram
atau bagan alur yang menjelaskan hubungan antara aktor, proses, dan luaran.
Pembahasan 3 :
Dibahas bagaimana
model ini dapat direplikasi atau dijadikan rujukan kebijakan dalam pengembangan
desa pesisir berbasis ekonomi sirkular, zero waste, dan teknologi lokal.
Disandingkan pula dengan tujuan SDGs, ekonomi biru, dan target pembangunan desa
mandiri.
Penutup
Kesimpulan
Penelitian ini
menunjukkan bahwa integrasi teknologi flying cam dan metode geofisika terapan
dapat menjadi pendekatan inovatif dan solutif dalam tata kelola limbah pesisir
berbasis potensi lokal. Limbah organik seperti cangkang kerang, kepah, dan
tulang ikan memiliki kandungan kalsium tinggi yang dapat diolah menjadi produk
bernilai tambah seperti pupuk granular, bio-material, atau suplemen pakan
ternak. Dengan dukungan pemetaan spasial dari drone dan analisis bawah
permukaan menggunakan resistivitas dan GPR, perencanaan pengelolaan limbah
menjadi lebih ilmiah, efisien, dan terukur.
Lebih jauh,
pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat pesisir – khususnya kelompok
perempuan – serta penerapan model kolaborasi Hepta Helix menjadi kunci
keberhasilan dalam membangun ekosistem inovasi lokal yang berkelanjutan. Kajian
ini membuktikan bahwa perpaduan antara sains, teknologi, dan pemberdayaan
sosial dapat mewujudkan desa pesisir yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing
dalam era ekonomi biru dan hijau.
Saran
Diperlukan
pelatihan berkelanjutan bagi masyarakat dalam penggunaan drone, teknologi
geofisika, dan pengolahan limbah agar transfer teknologi dapat berjalan
optimal.
Institusi
pendidikan tinggi dan lembaga riset hendaknya memperluas kemitraan dengan
desa-desa pesisir untuk memperkuat ekosistem riset terapan berbasis komunitas.
Diperlukan sistem
monitoring dan evaluasi berbasis data spasial dan sosial secara periodik untuk
memastikan keberlanjutan model pengelolaan limbah yang dibangun.
Rekomendasi
Bagi Pemerintah
Desa dan Daerah: Adopsi model ini sebagai bagian dari program desa berbasis
inovasi dan ekonomi sirkular, serta alokasikan anggaran untuk infrastruktur
pengolahan limbah dan edukasi teknologi.
Bagi Akademisi dan
Peneliti: Lanjutkan penelitian ini ke tahap hilirisasi produk dan standarisasi
proses produksi bahan berbasis kalsium dari limbah laut agar memiliki nilai
jual dan legalitas yang kuat.
Bagi Dunia Usaha
dan Investor Sosial: Dukung pengembangan UMKM pesisir berbasis limbah laut
melalui inkubasi usaha, CSR, dan kemitraan produksi yang menguntungkan semua
pihak.
Bagi Lembaga
Keuangan dan Filantropi: Fasilitasi akses permodalan mikro dan pendampingan
keuangan bagi komunitas pesisir dalam mengembangkan produk dari limbah sebagai
sumber penghidupan baru.(ms2)